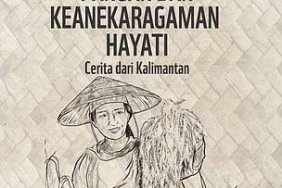SEKOLAH LAPANG PERTANIAN BERKELANJUTAN: BELAJAR DARI KEULETAN PETANI SUOH
Oleh: Hijrah Nasir
Terletak di Lampung Barat, Provinsi Lampung, Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Souh menyimpan potensi wisata yang besar, mulai dari keberadaan air terjun, danau, hingga kawah vulkanik yang berlantai batuan serupa marmer. Kedua kecamatan ini merupakan salah satu pintu masuk ke kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Masyarakat daerah ini menggantungkan hidup dari lahan yang mereka tanami dengan berbagai komoditas perkebunan, antara lain kakao, kopi, dan lada. Sebagian masyarakat juga bertani padi.
Menuju Souh masih memerlukan 7 jam perjalanan dari Kota Bandar Lampung. Dari Tanggamus, jalan mulai didominasi oleh tanah berbatu. Jejeran tanaman kopi, kakao, dan tanaman campuran lainnya berderet rapi. Beberapa rumah non-permanen dari kayu dibuat oleh penggarap lahan yang menanam kopi dan kakao. Beberapa pohon besar di kiri dan kanan jalan masih bisa ditemui saat kita melintas di Hutan Lindung Kota Agung Utara. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang datang ke sini, pohon-pohon diganti dengan tanaman perkebunan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya konservasi satwa kunci di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Berbekal hal tersebut, maka WWF bersama dengan mitra Rumah Kolaborasi melakukan pendampingan kepada masyarakat di Souh dalam mendukung upaya perlindungan habitat satwa kunci. Tahun 2016 menjadi awal pendampingan untuk pertanian padi dan kakao organik di desa-desa ini. Konsep sekolah lapang pertanian berkelanjutan diperkenalkan untuk mendorong masyarakat melakukan intensifikasi lahan pertanian mereka. Diharapkan dengan cara itu, masyarakat bisa mengurangi tekanan ke dalam hutan yang masih merupakan habitat penting dari satwa kunci, antara lain harimau sumatera, gajah sumatera, dan badak sumatera yang sudah dikategorikan ke dalam critically endangered species. Hal ini penting mengingat wilayah ini merupakan desa penyangga TNBBS. Satwa kunci yang keberadaannya semakin sedikit di alam mengalami berbagai ancaman karena perburuan, penyusutan habitat, dan konflik dengan masyarakat.
Ada 16 kali pertemuan dalam sekolah lapang padi organik yang dilaksanakan secara berkelompok ini. Jumlah petani yang berhasil dilibatkan adalah 85 orang yang berasal dari 6 desa. Salah satu hal yang membuat sekolah lapang pertanian berkelanjutan ini menarik adalah bagaimana mendorong petani di desa untuk menjadi subyek dari pemberdayaan yang dilakukan. Dengan satu pemahaman bahwa petani sudah memiliki pengetahuan bertani yang kaya yang mereka warisi secara turun temurun. Petani diajak untuk mencari tahu bagaimana alam bekerja dan mempengaruhi pola budidaya pertanian mereka. Dalam pertemuan tersebut mereka belajar konsep agro-ekosistem (agronomi dan hama penyakit), termasuk menganalisa dan mengambil tindakan dengan membuat pupuk sesuai pertumbuhan tanaman serta penanganan terhadap hama penyakit tanaman padi dengan pendekatan pertanian organik.
Berkat pelatihan sekolah lapang pertanian padi, petani yang awalnya menggunakan pestisida kimiawi secara berlebihan kini mulai beralih ke model pertanian ramah lingkungan. Namun pasca pelatihan, padi yang dihasilkan belum bisa disebut sebagai organic farming karena baru pada tahapan pengurangan penggunaan pupuk kimia dan digantikan dengan pupuk organik. Namun seiring dengan bertambahnya pengalaman petani dari serangkaian uji coba, mereka sudah berhasil memproduksi padi organik yang cukup diminati oleh pasar.
Berkat keuletan masyarakat, saat ini mereka aktif dalam kelembagaan petani yang mereka namai Komunitas Petani Lembah Souh. Mereka beranggotakan 42 orang yang berasal dari dua kecamatan yang sebelumnya mendapatkan pelatihan sekolah lapang pertanian organik. Lahan sawah seluas 25 Ha yang mereka garap mampu menghasilkan 5 – 6 ton/Ha di musim kemarau dan 6 – 7 ton/Ha di musim hujan dengan jenis padi pandan wangi, mentik susu, dan manalagi untuk beras putih, serta beras hitam dan beras merah lokal unggul. Dalam sebulan, kelompok mampu membeli rata-rata 1 ton beras siap jual dari anggotanya. Uniknya, masing- masing anggota punya nomor ID sendiri. Dan untuk menjaga kualitas beras yang seragam di antara anggota, masing-masing petani dianjurkan menjemur dan menggiling padinya selama dua hari. Ini dimaksudkan agar beras yang dihasilkan tidak pecah atau hancur saat digiling.
Ke depannya mereka berharap bisa meningkatkan produktivitas dan mampu membeli lebih banyak lagi beras organik dari petani. Mereka ingin kelompok juga punya penjemuran dan mesin penggiling sendiri sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan anggota komunitas tidak perlu mengolah sendiri padi mereka. Saat ini padi organik ini telah dipasarkan ke berbagai daerah, termasuk Bandar Lampung dan Liwa. Sebagian padi organik juga masih dijual di sekitar kecamatan.
Bertani secara organik telah berhasil meningkatkan harga dengan selisih 2.000 rupiah per kilogram. Selain memperbaiki kualitas lingkungan dan lebih sehat, bertani secara organik juga mampu meningkatkan nilai jual dan menurunkan biaya produksi yang menguntungkan bagi petani. Tantangan ke depan adalah mendorong petani untuk menularkan pengalaman budidaya padi organik yang sukses kepada lebih banyak orang di Suoh. Keberhasilan kelompok sekolah lapang cukup membantu proses sosialisasi bahwa metode ini akan berhasil dipergunakan pada pertanian organik tanaman lainnya.
Mengubah pola budidaya petani menjadi organik memang masih menemui jalan panjang. Namun seiring dengan meningkatnya permintaan pangan organik di kalangan konsumen menjadi angin segar bagi petani organik. Semoga Indonesia bisa belajar dari Sikkim, daerah kecil di kaki Pegunungan Himalaya yang berhasil menjadi 100% organik berkat kearifan dari masyarakatnya yang berhenti menggunakan pupuk dan pestisida kimiawi sejak 2016. Pola agro-ekologi ini telah berhasil meningkatkan pendapatan petani dan membuat pertanian mereka lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Dalam International Food Day 2018 ini, mari kita mendukung pola budidaya pertanian berkelanjutan.